Badriyah Fayumi Follow Alumnus Universitas al-Azhar Mesir; Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; Anggota Komisi Fatwa MUI; Pengasuh PP Mahasina Bekasi; Ketua Pengarah KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia)
1 min read
Assalamu’alaikum wr.wb. Ustazah saya ingin bertanya. Bagaimana hukum seorang istri yang berpura-pura bahagia berkeluarga demi anak-anaknya dan keluarga suaminya padahal dia sesungguhnya sangat menderita. Suaminya sering berselingkuh dan tidak mau memperbaiki diri. Suaminya juga jarang salat. Sang istri tidak lagi menganggap suaminya sebagai imam. Apakah istri demikian berdosa? Ibu Wanda [Nama Samaran]– Jakarta.
Wa’alaikumussalam wr.wb. Ibu Wanda yang dirahmati Allah. Dalam kasus di atas, yang jelas-jelas berdosa adalah suami. Dia selingkuh, membuat istri (dan tentu anak-anak) menderita, dan meninggalkan salat. Untuk istri, Insya Allah, dia akan mendapatkan ahala sabar karena pada dasarnya suami selingkuh dan meninggalkan salat adalah musibah.
Diharapkan kesabaran istri tidak hanya pasrah, tapi aktif juga mengajak suaminya bertobat dan istri sendiri tetap berada di jalan yang benar, serta tidak terpancing melakukan perbuatan dosa karena “balas dendam” kepada suaminya. Itulah sabar yang ideal.
Berpura-pura bahagia demi anak-anak dan keluarga suaminya, Insya Allah bukanlah dosa karena tidak ada pihak lain yang dirugikan dengan sikap itu. Hal tersebut malah sebuah pengorbanan istri demi keselamatan keluarga. Dalam kasus seperti ini berlaku kaidah al-tsawāb bi qadri al-ta‘ab (pahala sesuai dengan kadar kelelahan/pengorbanan).
Ada dua pilihan Alquran yang perlu diketahui oleh istri dalam keadaan seperti ini, tanpa ada celaan. Pertama, istri yang suaminya berpaling dan nusyūz (meninggalkan kewajiban) diberi pilihan menempuh langkah “berdamai” (shulh), dengan landasan ihsān (ingin tetap melakukan yang lebih baik) dan takwa (Surah al-Nisā’ [4]: 128). Alquran sendiri mengakui shulh ini baik, tapi berat.
Kedua, istri diberi pilihan untuk bercerai dan Allah berjanji akan memberikan rezeki kepada hamba-Nya (surah al-Nisā’ [4]: 130). Ingin pilihan yang mana, semua kembali kepada istri.
Mana yang lebih maslahat untuk diri dan anak-anaknya. Mungkin jika anak-anaknya sudah dewasa dan situasi tidak berubah, mereka bisa diminta pertimbangan. Namun, suami semoga saja segera bertobat dari perbuatannya.
Mengenai suami sebagai imam dalam keluarga, yang saya pahami dalam surah al-Nisā’ [4]: 34 adalah bahwa kepemimpinan suami dalam keluarga memerlukan terpenuhinya dua syarat, yakni pemberian nafkah dan perlindungan keluarga, serta kemampuan lebih yang dimilikinya (untuk layak dijadikan imam).
Dengan demikian keimaman suami tidaklah bersifat mutlak, permanen, dan tanpa syarat. Itu sesuai dengan arti surah al-Nisā’ [4]: 34, “Suami adalah pelindung istri, karena Allah telah melebihkan sebagian (suami) atas sebagian yang (istri), dan karena mereka telah memberi nafkah dari sebagian hartanya ….”.
Dari penggalan ayat ini ada dua hal penting yang bisa kita simpulkan. Pertama, keimaman suami tergantung dari kelebihannya yang menjadikannya mempunyai kapasitas sebagai pemimpin dan pelindung keluarga, dan kesanggupannya memberi nafkah (lahir dan batin).
Kedua, tidak semua suami mampu menjadi qawwām (pelindung), karena sebagian sumai memenuhi kedua syarat di atas, sebagian yang lain tidak.
Dari tafsir ayat ini, jika dikaitkan dengan kasus di atas, tidak dapatnya istri menganggap suaminya sebagai imam karena perilaku suaminya adalah hal yang ajar. Suamilah yang seharusnya bertobat sehingga layak disebut dan dianggap imam oleh keluarganya.
Editor: MZ
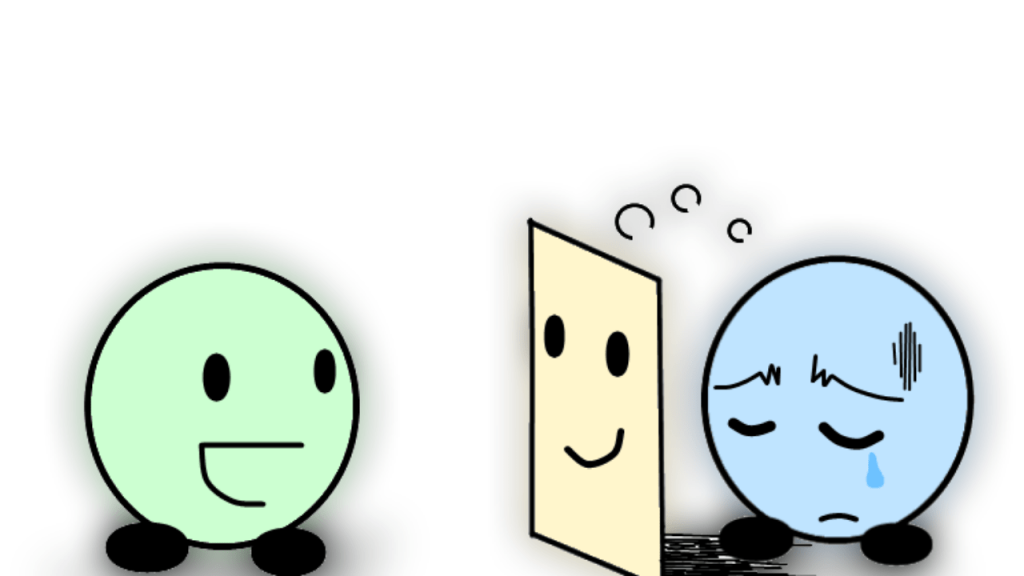








![[TOTAL BIAYA] GUNUNG PRAU VIA PATAK BANTENG || PANDUAN TRANSPORTASI KE BASECAMP PATAK BANTENG](https://kabarwarga.com/wp-content/uploads/2024/11/49446-total-biaya-gunung-prau-via-patak-banteng-panduan-transportasi-ke-basecamp-patak-banteng-150x150.jpg)
